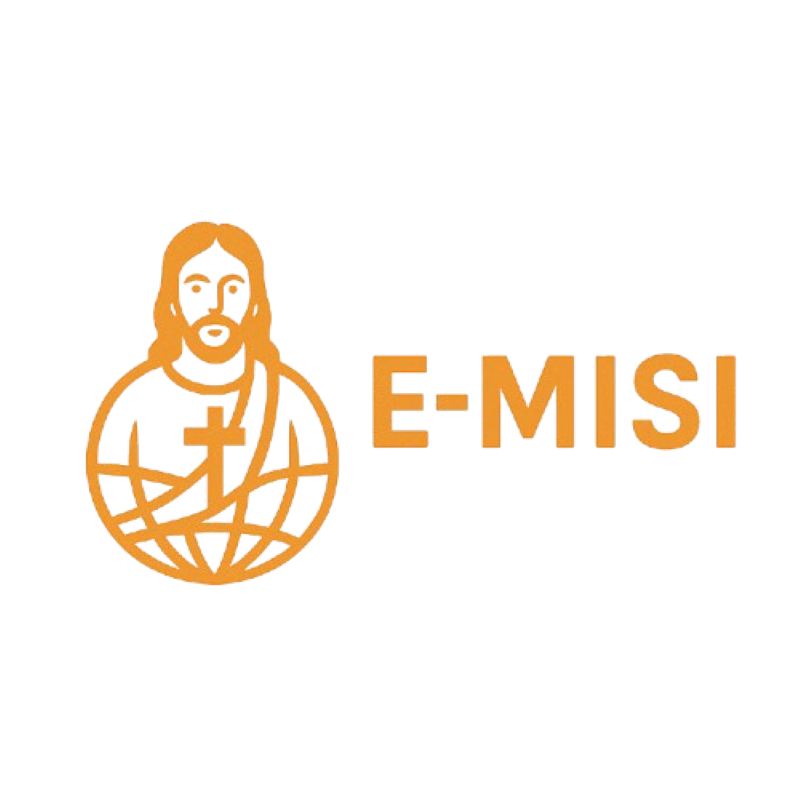MISIONARIS WANITA LAJANG: "WARGA KELAS DUA"
Sejak dahulu, wanita sudah memiliki peran dalam dunia penginjilan. Dari zaman Perjanjian Baru, gereja mula-mula dan zaman Abad Pertengahan, sampai ke periode misi modern, pelayanan wanita sangat luar biasa. Para istri Moravia bahkan sangat menonjol dan berdedikasi terhadap dunia pelayanan, seperti juga para istri misionaris (misalnya, Adoniram Judson dan Hudson Taylor). Namun, ada juga para istri yang setia melayani meski sebenarnya tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah istri yang tetap setia melayani meskipun itu bukanlah yang mereka ingini. Edith Buxton, dalam bukunya "Reluctant Missionary" (Misionaris yang Enggan), mengisahkan perjuangan dan ketidakbahagiaannya menjalani kehidupan sebagai seorang misionaris asing sebelum akhirnya ia mengetahui bahwa pelayanan ini adalah kehendak Tuhan; serta Pearl Buck yang mengisahkan tahun-tahun penuh ketidakbahagiaan yang dijalani ibunya sebagai istri seorang misionaris di Cina, sebelum akhirnya dia dapat menerima pekerjaannya.
Sebaliknya, ada jauh lebih banyak wanita lajang yang merasa bahwa Tuhan memang menginginkan mereka bekerja di ladang misi. Mereka merasa tertantang dengan adanya tuntutan yang besar di dunia luar. Para istri, dengan segala tanggung jawab rumah tangga dan anak yang harus dirawatnya, tentu tidak sanggup menanggung beban ini. Walaupun publik menentang mereka berkecimpung dalam ladang misi, pada awal tahun 1820-an, satu per satu wanita lajang mulai merambah ke luar negeri.
Wanita lajang berkebangsaan Amerika (bukan janda) pertama yang menjadi misionaris asing adalah Betsy Stockton. Ia adalah seorang wanita kulit hitam dan bekas budak yang pergi ke Hawaii pada tahun 1823. Ia bergabung dengan American Board dan mereka setuju untuk mengirimnya ke luar negeri, namun hanya sebagai pembantu lokal untuk pasangan misionaris lain. Terlepas dari rendahnya posisi itu, Betsy dianggap memiliki kemampuan untuk mengajar sehingga diizinkan untuk merintis satu sekolah. Menanggapi kebutuhan akan seorang guru wanita lajang, Chyntia Farrar yang berasal dari New Hampshire, bertolak ke Bombay pada tahun 1820-an. Ia melayani dengan setia selama 34 tahun di bawah naungan badan Marathi Mission.
Diskriminasi terhadap wanita lajang menyebabkan munculnya konsep baru tentang misionaris asing, yaitu "lembaga wanita". Persepsi ini pertama kalinya muncul di Inggris dan dengan cepat menyebar sampai ke Amerika. Sampai tahun 1900, ada lebih dari empat puluh kelompok misi wanita di AS. Karena adanya "lembaga wanita" ini, jumlah wanita lajang di ladang misi meningkat pesat, bahkan melampaui jumlah misionaris pria. Di Provinsi Shantang, Cina, data statistik yang berkaitan dengan Lembaga Baptis dan Presbytarian menunjukkan ada 79 wanita berbanding 46 pria. Pada dekade selanjutnya, perbandingan itu meningkat menjadi 2:1.
Dalam bukunya, "Western Women in Eastern Lands" (Wanita Barat di Tanah Timur) yang diterbitkan tahun 1910, Helen Barret Montgomery mengisahkan langkah mengagumkan yang dilakukan para wanita di dunia penginjilan.
"Benar-benar cerita yang mengagumkan .... Kami memulai semua ini dalam ketidakberdayaan, namun kini kami dikuatkan. Pada tahun 1861, hanya ada seorang misionaris bernama Miss Marston di Burma. Tahun 1909 ada 4.710 misionaris wanita lajang, 1.948 di antaranya berasal dari AS. Tahun 1861 hanya ada satu organisasi wanita, namun telah berkembang menjadi 44 pada tahun 1910. Pendukungnya semula hanya beberapa ratus, tapi kini mencapai sedikitnya dua juta orang. Dana yang tersedia awalnya hanya dua ribu dolar dan tahun 1982 meningkat menjadi empat juta dolar. Dan kalau awalnya hanya ada seorang guru, pada awal tahun Yobel mencapai 800 guru, 140 dokter, 380 penginjil, 79 perawat, 5.783 wanita pengajar Alkitab dan pembantu asli (native). Dari 2.100 sekolah, ada 260 sekolah tinggi dan sekolah asrama. Ada 75 rumah sakit dan 78 apotek .... Ini suatu prestasi yang patut dibanggakan para wanita. Namun, ini hanyalah permulaan yang sederhana dari apa yang bisa dan yang mampu dikerjakan wanita, di saat kegerakan siap dimulai."
Namun, apa yang sebenarnya mendorong para wanita lajang itu sehingga rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya, bahkan hidup dalam kesulitan, kesendirian, dan pengorbanan? Tampaknya alasan terbanyak adalah karena kecilnya kesempatan bagi wanita lajang untuk melayani sepenuh waktu di tanah air mereka. Pelayanan Kristen dianggap sebagai pekerjaan pria. Beberapa wanita dari abad ke-19, seperti Catherine Booth, mencoba terjun ke dalam dunia yang didominasi oleh para pria ini, namun juga mendapat tentangan. Wanita lainnya bekerja di dunia sekuler. Florence Nightingale misalnya, sangat rindu untuk melayani Tuhan dalam pelayanan Kristen, tapi tidak mendapat kesempatan. Itulah alasan mengapa ladang misi menjadi wadah bagi para wanita yang ingin melayani Tuhan.
Selain itu, ladang misi juga penuh dengan pelayanan dan semangat yang menyala-nyala. Wanita dari golongan miskin pun bisa terangkat statusnya melalui karier misionaris ini. Namun, pengaruh yang paling kuat adalah feminisme. Masuknya wanita Amerika ke dalam dunia misi, menurut R. Pierce Beaver, dianggap sebagai gerakan feminis pertama di Amerika Utara. Meski sebagian besar misionaris wanita bukan penganut feminisme, usaha mereka untuk menyelami dunia pria adalah bukti adanya rasa kesetaraan antara wanita dan pria yang sedikit banyak dibantu oleh perkembangan "lembaga wanita".
Wanita lajang memiliki kesempatan unik yang tidak dapat dilakukan pria. Injil bisa menembus ke dalam budaya dan agama kuno adalah karena pekerjaan wanita (meskipun tak dapat disangkal juga bahwa di beberapa daerah, wanita hanya bisa bekerja bila sudah ada pria yang memulainya terlebih dulu). Selain itu, wanita juga tidak terikat tanggung jawab terhadap keluarga. Menanggapi kebebasan tersebut, H. A. Tupper, sekretaris Southern Baptist Foreign Mission Board (Lembaga Misi Baptis Selatan) menyurati Lottie Moon pada tahun 1879, "Pekerjaan seorang wanita lajang di Cina setara dengan dua pria yang sudah menikah." Namun, karena merasa kesepian, tekanan, dan kondisi yang buruk, banyak misionaris wanita lajang yang menyerah dan meninggalkan ladang misinya.
Wanita memang lebih unggul di hampir semua aspek dunia misionaris, tapi dalam bidang medis, pendidikan, dan penerjemahan, kemampuan mereka sangat berpengaruh. Rumah sakit dan sekolah kedokteran adalah dua di antara banyak hasil yang diraih, termasuk di antaranya salah satu sekolah medis terbaik di dunia yang berlokasi di Vellore, India. Mereka juga mendirikan banyak sekolah lainnya, termasuk sebuah universitas di Seoul, Korea, dengan jumlah mahasiswa yang mencapai delapan ribu orang. Kitab Injil untuk pertama kalinya diterbitkan dalam ratusan bahasa asing. Namun, jika ada satu generalisasi yang bisa ditarik dari misionaris wanita dan pelayanannya, itu adalah tekad mereka untuk merintis pelayanan yang sulit. "Semakin sulit dan berbahaya suatu pelayanan, rasio wanita dibanding pria akan semakin tinggi," tulis Herbert Kane.
Keunikan wanita dalam dunia pelayanan adalah mereka umumnya lebih mudah mengakui kelemahan dan menerima kritikan. Mereka juga lebih mewakili kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan. Lottie Moon, Maude Carys, dan Helen Roseveares memberikan pemahaman tentang kehidupan misi modern kepada para murid. (t/Lanny)
Bahan diringkas dan diterjemahkan dari sumber:
| Judul buku | : | From Jerusalem to Irian Jaya |
| Judul asli | : | Single Woman Missionaries: "Second-class Citizens" |
| Penulis | : | Ruth A. Tucker |
| Penerbit | : | Academie Books, Grand Rapids, Michigan 1983 |
| Halaman | : | 231 -- 234 |
Edisi e-JEMMi
Kategori
Kolom Publikasi
- Printer-friendly version
- Log in to post comments